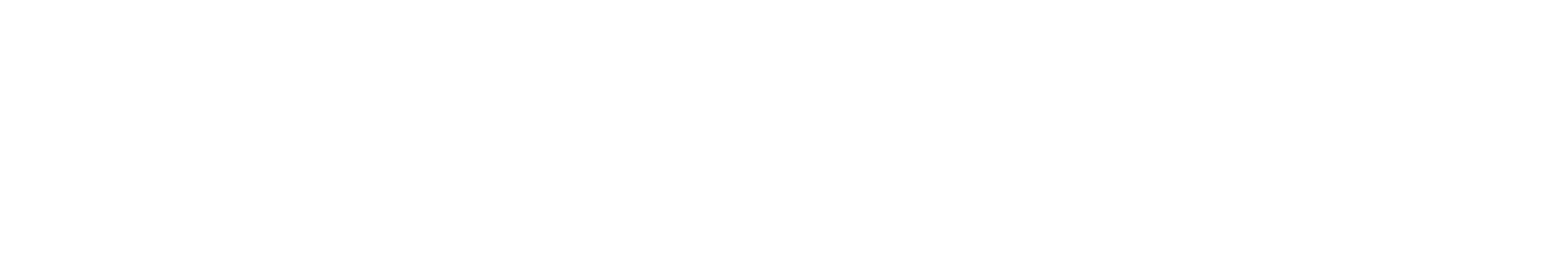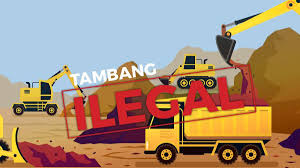Mengenal HAB Tentang Air Laut Berubah Warna

 |
| M GHUFRAN H. KORDI K. |
Seorang kawan mengirimkan
foto mengenai air laut berubah warna merah/coklat dan ikan-ikan yang mati di
Pulau Makean, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada
24 Februari 2020 dan menjadi tontonan warga.
Perubahan warna air tersebut
bisa disebabkan oleh pencemaran, bisa juga karena ledakan plankton yang dikenal
sebagai Harmful Algal Bloom (HAB). Untuk memastikannya perlu dilakukan
pemeriksaan terhadap ikan-ikan yang mati dan analisis kualitas air. Tulisan ini
hendak mengenalkan peristiwa alam yang dikenal sebagai ledakan plankton,
khususnya fitoplankton atau populer sebagai Harmful Algal Bloom (HAB).
Istilah HAB kini menjadi
istilah yang digunakan di dunia internasional yang merupakan singkatan dari
Harmful Algal Bloom. HAB adalah istilah generik yang digunakan untuk mengacu
pada pertumbuhan lebat fitoplankton di laut atau di perairan payau yang dapat
menyebabkan kematian massal ikan, mengontaminasi makanan bahari (seafood)
dengan toksin (racun yang diproduksi oleh fitoplankton), dan mengubah ekosistem
sedemikian rupa yang dipersepsikan oleh manusia sebagai mengganggu (harmful)
(Geohab, 2000; Nontji, 2008).
Sebelumnya fenomena ini
dikenal sebagai red tide untuk menggambarkan ledakan populasi fitoplankton ini
yang dapat mengubah warna air laut. Tetapi isitilah ini sering menyesatkan
karena tidak selalu ledakan populasi fitoplankton ini berwarna merah (red),
bisa juga kuning, hijau, hijau kuning, merah kecoklatan, atau putih keruh.
Bergantung pada pigmen yang terkandung dalam fitoplankton penyebabnya. Lagi
pula, ledakan populasi fitoplankton ini tidak berkaitan dengan tide alias
pasang surut.
Selanjutnya juga tidak semua
jenis plankton yang populasinya meledak itu memroduksi toksin atau racun.
Meskipun demikian, ledakan populasi fitoplankton yang nontoksik ini bisa juga
berbahaya bila setelah mati massal akan terurai oleh bakteri. Dalam proses
penguraian ini diperlukan konsumsi oksigen yang tinggi hingga dapat membuat
oksigen yang terlarut dalam air akan habis terkuras, dan menimbulkan kondisi
anoksik, kehabisan oksigen. Ketiadaan oksigen dalam air inilah yang dapat
mengancam kehidupan biota lainnya, seperti ikan dan hewan laut lainnya (Nontji,
2008).
Di Indonesia, fenomena HAB
pertama kali dilaporkan terjadi tahun 1976 di Teluk Kao, Halmahera (Maluku
Utara) yang menyebabkan jatuhnya korban manusia, yang oleh penduduk setempat
menyebutnya air beracun berwarna merah (Sumadiharga, 1977). Kemudian terjadi
lagi tahun 1983 Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada saat itu Gubernur NTT Ben Boy
melaporkan adanya peristiwa keracunan dan kematian massal penduduk setelah
memakan ikan yang mati mengamban di permukaan perairan pantai Selat Lewotobi,
Desa Wulanggitang, Flores Timur NTT. Dilaporkan 240 orang orang keracunan dan 4
orang meninggal (Adnan, 1984). Setelah dilakukan penelitian dengan memeriksa
sampel ikan dan air laut yang diambil pada saat kejadian, diketahui bahwa
penyebab HAB adalah blooming Pyrodinium bahamenses var. compressum.
Fitoplankton Pyrodinium bahamenses var. compressum merupakan penyebab HAB utama
di Pasifik Selatan termasuk di perairan negara-negara di Asia Tenggara.
HAB oleh Pyrodinium
bahamense var. compressum yang terjadi di perairan Indonesia sangat jelas
mempunyai keterkaitan dengan kejadian-kejadian HAB di negara-negara di Asia Tenggara
bersamaan dengan terjadinya El Nino. Tahun 1983 pada saat blooming terjadi di
Flores, di mana 240 orang keracunan dan 4 orang meninggal, di Teluk Samar dan
Teluk Maquenda, Filipina juga sedang terjadi HAB, tepatnya Juni-September.
Penyebab HAB sama dan mengakibatkan 278 orang keracunan/menderita dan 21 orang
meninggal. Demikian juga di perairan Hongkong yang terjadi pada bulan Oktober
1983 dengan laporan keracunan makan kerang dan ikan mati. HAB yang terjadi di
Nunukan, Pulau Sebatik Selatan, Kalimantan Timur 1987 juga terjadi bersamaan
waktuya dengan kejadian yang sama d Sabah (Malaysia). Semua kejadian HAB baik
di Indonesia maupun di Asia Tenggara ternyata ternyata bersamaan waktunya
dengan terjadinya ENSO (El Nino) pada 1983, 1987, dan 1988. Dengan demikian,
kejadian HAB baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara umumnya sangat berkaitan
dengan fenomena alam El-Nino yang merupakan salah satu tanda terjadinya “global
climate change” di dunia (Adnan & Sidabutar, 2004).
Tabel 1. Jenis mikroalgae
pembentuk HAB yang terdentifikasi di perairan Indonesia
|
No |
Jenis Mikro-Algae |
Lokasi |
|
1 |
Alexandrium |
Teluk |
|
2 |
Alexandrium |
Teluk |
|
3 |
Alexandrium |
Teluk |
|
4 |
Ceratium fusus Teluk |
Teluk Jakarta, Teluk Bayur, Ujungpandang/Makassar, |
|
5 |
Ceratium |
Teluk |
|
6 |
Chattonella |
Teluk |
|
7 |
Dinophysis |
Teluk |
|
8 |
Dinophysis |
Teluk |
|
9 |
Dinophysis |
Teluk |
|
10 |
Dinophysis |
Teluk |
|
11 |
Dinophysis |
Teluk |
|
12 |
Dinophysis |
Teluk |
|
13 |
Gambierdiscus |
Flores |
|
14 |
Gonyaulax |
Teluk |
|
15 |
Gonyaulax |
Ujungpandang/Makassar |
|
16 |
Gonyaulax |
Teluk |
|
17 |
Gonyaulax |
Teluk |
|
18 |
Gymnodinium |
Teluk |
|
19 |
Gymnodinium |
Teluk |
|
20 |
Gymnodinium |
Tambak |
|
21 |
Gymnodinium |
Flores |
|
22 |
Noctluca |
Teluk |
|
23 |
Prorocentrum |
Flores |
|
24 |
Prorocentrum |
Teluk |
|
25 |
Prorocentrum |
Teluk |
|
26 |
Prorocentrum |
Teluk |
|
27 |
Prorocentrum |
Teluk |
|
28 |
Prorocentrum |
Teluk |
|
29 |
Pseudonitzschia |
Teluk |
|
30 |
Pyrodinium |
Teluk online pharmacy with fast delivery how to purchase clomiphene online with the lowest prices today in the USA
ur |
|
31 |
Trichodesmium |
Pantai |
|
32 |
Trichodesmium |
Kalimantan |
|
33 |
Ostreopsis |
Teluk |
|
35 |
Ostreopsis |
Teluk |
|
35 |
Thalasisiosira |
Teluk |
Sumber: Adnan (1984; 1992;
1999); Praseno (1997; 19999); Adnan & Sidabutar (2005)
Keterangan: * mikroalgae
berpotensi menghasilkan toksin; ** mikroalgae menimbulkan masalah bagi
perikanan.
Biota penyebab HAB
menghasilkan toksin dalam tubuhnya yang kemudian toksin tersebut dapat
dialihkan ke ikan atau kerang lewat jalur pakan (food chain). Kehadiran bahan
toksik di dalam tubuh kerang bisa saja tidak menimbulkan kematian pada kerang
tersebut, tetapi bila dimakan oleh manusia akan dapat menimbulkan gangguan
kesehatan bahkan kematian. Orang yang memakan makanan laut yang terkontaminasi
toksin HAB dapat menderita keracunan, bergantung jenis toksin yang diproduksi
biota HAB.
Fitoplankton jenis Pyrodinium
bahamense dan Alexandrium tamarense misalnya menghasilkan racun saxitoxin yang
dapat menimbulkan gejala Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) yang mengakibatkan
penderita kejang-kejang sampai kelumpuhan setelah makan kerang. Dalam kasus
yang sangat gawat dapat mengakibatkan penghentian fungsi pernapasan dalam waktu
24 jam setelah penderita mengonsumsi kerang.
Gejala keracunan lainnya
adalah Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP) yang menimbulkan diare yang
disebabkan racun okadaic acid yang dihasilkan oleh fitoplankton jenis
Dinophysis sp. Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP) disebabkan oleh racun
brevetoxin yang dihasilkan oleh fitoplankton jenis Karenia brevis yang
menimbulkan serangan pada saraf. Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) disebabkan
oleh racun domoic acid yang diproduksi oleh Pseudonitzshia sp yang dapat
menimbulkan gangguan gatroinsestinal dan saraf setelah penderita mengonsumsi
kerang. Keracunan juga dapat ditimbulkan karena orang mengonsumsi ikan yang
terkontaminasi racun ciguatoxin/maitotoxin yang bersumber dari fitoplankton
Gambierdiscus, Prorocentrum, Amphidinium yang menimbulkan gejala Ciguatera Fish
Poisoning (CFP). Sebenarnya diantara ribuan jenis fitoplankton yang telah
dikenal, hanya beberapa saja yang berbahaya (Nontji, 2008)
Selain menimbulkan gangguan
pada lingkungan dan kesehatan manusia, HAB juga dapat menimbulkan kerugian
ekonomi. Berita HAB yang tersebar di media dapat menyebaban turunnya omzet
perdagangan hasil-hasil perikanan karena orang menjadi takut mengonsumsi seafood.
HAB yang terjadi di suatu tempat akuakultur dapat menimbulkan kerugian yang
amat besar. HAB yang disebabkan oleh Pyrodinium bahamense yang menyerang Teluk
Manila (Filipina) tahun 1988 menimbulkan kerugian US$ 950.000 pada budi daya
tiram, US$ 500.000 perhari pada ekspor udang, 809.000 selama 4 hari pada
perikanan tangkap, US$ 300.000 perhari pada pasar seafood. Hongkong pernah
dilanda HAB yang besar pada Maret-April 1998 yang disebabkan meledaknya
plankton jenis Gymnodinium mikimotoi. Serangan ini luar biasa dahsyatnya bagi
perikanan Hongkong yang mematikan 1.500 ton ikan budi daya dan menimbulkan
kerugian ekonomi sekitar US$ 32 juta. Kematian massal ikan ini disebabkan
karena Gymnodinium mikimotoi yang menghasilkan lendir (mucus) yang lengket
menempel pada semua benda di laut termasuk menempel pada insang-insang ikan
sehingga ikan tersebut tidak dapat bernapas dalam waktu sekejap saja (Nontji, 2008; Rompas, 2010).
Mikroalga kelompok HAB
penghasil toksin (racun) yang diduga mengalami ledakan populasi (blooming)
karena eutrofikasi yang terkait dengan aktivitas budi daya perairan yaitu
spesies Pyrodinium bahamense var compressum di Teluk Lampung. Teluk Lampung
merupakan teluk dangkal dengan kedalaman rata-rata 25 m dengan kondisi perairan
yang relatif tenang. Teluk ini mendapat tekanan yang cukup tinggi dari
aktivitas manusia, baik di bidang pariwisata, industri, maupun kegiatan
marikultur dan tambak.
Spesies mikroalga yang
menimbulkan HAB tidak semuanya beracun. Dua spesies HAB, yaitu Noctiluca spp
dan Trichodesmium spp tidak beracun, tetapi setelah blooming dan mati mengalami
dekomposisi yang mengonsumsi oksigen, mengeluarkan amoni
a, dan mengubah warna
air laut menjadi merah (red tide). Kondisi demikian menyebabkan ikan-ikan dan
biota lainnya mati. Selain menimbulkan gangguan pada lingkungan dan kesehatan
manusia, HAB juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Berita tentang HAB dapat
menyebabkan turunnya omset perdagangan biota laut. HAB yang melanda suatu
perairan tempat budi daya laut dapat menimbulkan kerugian yang amat besar.
Hingga sekarang ini hanya
sedikit anggota masyarakat yang sadar akan bahaya HAB. Peneliti yang serius
menangani masalah ini di Indonesia pun sangat terbatas jumlahnya, yang tersebar
di lembaga penelitian, seperti LIPI, Balai Budidaya Laut (DKP), Balai
Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (DKP), dan universitas (UI).
Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, merupakan lembaga yang
secara rutin melakukan monitoring HAB di Teluk Hurun dan merupakan pilot untuk
Indonesia dengan dukungan IOC/Westpac.
HAB adalah peristiwa alam
yang berhubungan cuaca. Namun, HAB juga dipicu oleh aktivitas manusia di
daratan dan di lautan. Pengayaan nutrien, seperti halnya nitrat dan fosfat,
selain berasal dari zat hara daratan (run off), juga dapat disebabkan dari
aktivitas budi daya di pantai. Begitu pula pemindahan biota budi daya, seperti
kima dan kerang/tiram dari satu daerah ke daerah lain juga dapat menyebabkan
tingginya resiko “terinfeksi” suatu perairan karena terbawanya jenis-jenis
mikroalga berbahaya yang berasal dari perairan lain.
Untuk menghindari bahaya,
masyarakat tidak boleh mengonsumsi ikan-ikan yang mati. Masyarakat juga tidak
mengambil dan mengonsumsi kerang/siput yang berada di daerah HAB dan
sekitarnya[]