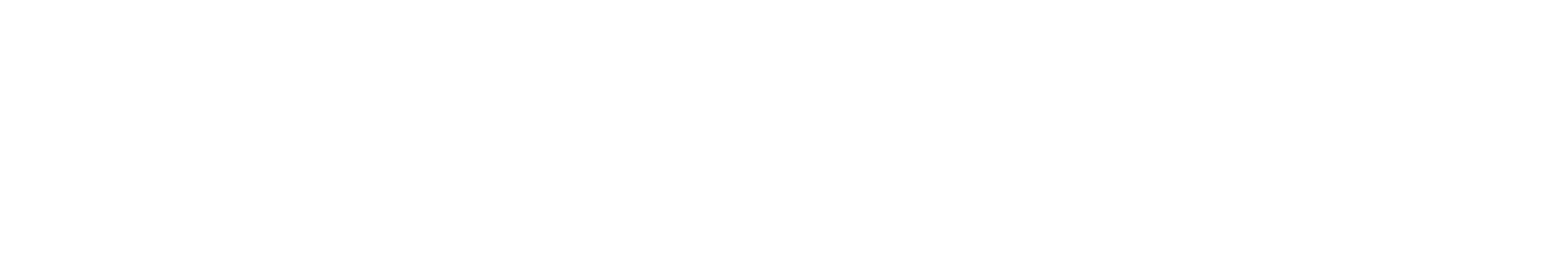Birokrasi dan Tujuan Mulia Pelayanan Publik

 |
|
Oleh: Dr. *Rektor Universitas |
Memulai
topik ini, alangkah baiknya dipaparkan data awal tentang Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menempatkan Aparatur Sipil
Negara (ASN) sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada
2010-2016. Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan
sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah. Demikian pula laporan The Global Competitiveness Report 2016-2017,
menempatkan Indonesia urutan peringkat ke-41 dari 138 negara, dan bahkan masih
berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.
Data ini tidak mengejutkan
bagi publik karena inefesiensi dan korupsi memang telah menjadi penyakit kanker
yang sedang menggerogoti siklus dan aktivitas birokrasi pemerintahan dewasa ini
(Kompas,7/4/2017). Bagaimana mungkin birokrasi mampu menyelenggarakan pelayanan
publik yang baik jika masih dililit dengan mentalitas demikian.
Sekurangnya-kurangnya birokrasi memposisikan kelembagaannya pada tiga hal
mendasar yaitu sejauh mana kemampuan birokrasi dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik, bebas korupsi dan akuntabilitas kinerja. Baik buruknya kualitas
pelayanan publik dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat, bebas KKN dapat
diukur melalui integritas dan indeks persepsi korupsi masyarakat. Sedangkan akuntabilitas kinerja dapat dikuru melalui nilai
laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Ketidakpuasan
masyarakat terjadi dimana-mana. Keluhan, kekecewaan dan protes masyarakat
seringkali dialamatkan pada birokrasi. Fenomena ini menjadi pertanda awal dalam
menilai birokrasi dari sisi tingkat kepuasan masyarakat. Lebih banyak muncul
imaginasi bahwa proses birokrasi dianggap berbelit dan cenderung mempersulit
masyarakat. Apakah memang benar demikian. Untuk dapat menepis anggapan itu,
sekruang-kurangnya birokrasi memperbaiki dirinya dalam membenahi kualiats pelayanan
publik. Birokras yang melayani, dan bukan dilayani. Birokrasi yang mampu memberi pelayanan publik
secara efisien, efektif, dan produktif.
membangun budaya etika publik. Guna
mencapai model pelayanan publik itu,
birokrasi idealnya dalam praktek pelayanannya menjadikan Etika publik sebagai nilai luhur.
Etika publik adalah suatu keinginan yang disematkan kepada birokrasi agar
bertindak di bawah rambu-rambu akuntabilitas,
transparansi, dan integritas. Semuanya harus melekat pada tubuh birokrasi, baik
dari level terdepan (street Level
bureaucracy) sampai pada puncak atasan birokrat.
Kemampuan
birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik memerlukan kepekaan dan
hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan baik yang
member pelayanan maupun pihak yang dilayaninya. Makna pelayanan lebih mengarah pada bentuk pengabdian kepada
masyarakat karena birokrasi telah diberi tunjangan pemerintah. Segala bentuk
pelayanan publik yang dilakukan birokrasi pada umumnya berupa barang-barang
publik (public goods) untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat selalu menginginkan beberapa hal yaitu,
bagaimana seharusnya briokrasi dalam melayani masyarakat dengan cara yang sederhana,
jelas, pasti, aman, terbuka, efisien, murah, adil dan tepat waktu. Jika suatu
pelayanan itu sebenarnya lebih mudah dilakukan, buat apa menempuhnya dengan
cara yang lamban, berbelit-belit dan mempersulit keadaan. Jika birokrasi itu
sudah jelas tupoksinya (tugas pokok dan fungsi), memiliki kejelasan prosedur
dan regulasinya, lantas untuk apa sengaja tidak menempuh prosedur baku.
Kejelasan prosedur dan regulasi
dalam birokrasi justru seharusnya lebih mempermudah pelayanan karena mampu
mencapai sasaran pelayanan tersebut. Namun seringkali dalam mencapai sasaran
pelayanan publik, oknum birokrasi menelikung menggunakan jalur pelayanan cepat
namun disertai dengan biaya mahal. Mal Praktek ini justru akan merusak tujuan
mulia pelayanan publik. Seringkali upaya pelayanan harus ditebus dengan uang
pelicin melebihi tarif yang ditetapkan. Akibatnya pelayanan publik menjadi
tidak ekonomis, murah dan procedural. Pertanyaannya, apakah sedemikian sulitnya
birokrasi mewujudkan pelayanan pubik. Di beberapa Negara-negara maju dengan
tradisi Birokrasi Weberian yang kuat, penerapan etika publik bagi pelayan
publik diwajibkan memenuhi unsur-unsur penting, pertama, apakah sudah
diterapkan model pelayanan yang merata dan sama, tidak diskriminatif, tidak menganakemaskan
keluarga, pangkat, suku, dan agama, ataupun status social. Kedua, apakah
pelayanan yang diberikan mampu diselesaikan tepat pada waktunya, dan ketiga
apakah pelayanan yang diberikan itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh
masyarakat. Pertanyaan terakhir ini sangat perlu direnungkan karena banyak
pelayanan publik yang mubazir, tidak bisa dimanfaatkan, tidak berdampak
ekonomis dan salah sasaran.
Seringkali ketidakadilan dalam
pelayanan publik itu muncul karena perilaku diskriminasi birokrat yang
memposisikan dirinya sebagai bagian dari wibawa penguasa. Berbagai pengalaman setelah
usai pemilihan kepala daerah (Pilkada) seringkali memposisikan produk layanan
publik tidak merata dan pilih kasih di masyarakat sebagai sebagai akibat dari rendahnya
integritas dalam memahami makna Negara dan fungsi pemerintahan. Apakah
pelayanan publik itu berupa Pelayanan administratif, pelayanan barang
maupun pelayanan jasa masih sering dipolitisasi berdasarkan kecenderungan dan
selera penguasa. Padahal penguasa pun masih dikategorikan sebagai pelayan
publik dan harus mampu memberi jaminan kualitas pelayanan publik.
Praktek pilih kasih dalam pelayanan publik
ini akan merusak etika publik karena menghilangkan kesadaran para pejabat maupun PNS dari tanggung
jawabnya yang diberikan oleh Negara terhadap pengakuan sumpah jabatannya,
bersifat munafik di hadapan Tuhannya karena ketidak ikhlasannya dalam melayani
masyarakat tertentu. Padahal kepercayaan public yang diberikan oleh mayoritas
pemilih seharusnya dibalas dengan pengabdian untuk semua kalangan tanpa
membeda-bedakan perbedaan pilihan. Apakah kebijakan politik yang rasis dan sepihak
ini akan selama-lamanya mengalahkan etika publik. Jika skenario pelayanan
publik ini ditempuh akan menimbulkan
ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Padahal Negara telah membangun birokrasi dan seluruh alat kelengkapannya demi
melayani seluruh masyarakat sesuai dengan cita-cita bernegara dan
penyelenggraan pemerintahan.
Birokrasi
ASN diberi tanggung jawab yang mulia dalam melakukan pelayanan publik. petunjuk
teknisnya dapat dilihat pada Pasal 23 UU 5/2014 tentang ASN bahwa setiap ASN
wajib menjaga sikap dan perilaku, kepatuhan, kerahasiaan, komitmen dan
loyalitas, konsistensi terhadap seluruh tugas-tugas yang diembannya. Demikian
pula setia ASN diberi peringatan tentang larangan yaitu Penyalahgunaan wewenang, pencemaran lembaga,
gratifikasi, rangkap jabatan dan konflik kepentingan. Tidak terlepas dari
kewajiban dan larangan, ASN juga wajib memenuhi nilai dasar kode etik dan kode
perilaku; komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; kualifikasi akademik; jaminan
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan. Nilai
dasar itu menjadi bekal dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jika dikomparasikan kualitas
pelayanan publik pemerintah dan lembaga-lembaga swasta korporasi dan berbagai
lembaga swadaya masyarakat, seringkali
birokrasi pemerintah jauh te
rtinggal dari lembaga swasta. UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik member standar baku pelayanan publik
bagi penyelenggara seperti kepentingan umum, kepastian hokum, kesamaan hak,
keseimbangan hak dan kewajiban,
keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,
keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Sasaran
pelayanan publik ditekankan adalah sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,
jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata,
dan sektor strategis lainnya. Beberapa sektor pelayanan publik tersebut sangat penting bagi hajat hidup
banyak orang sehingga membutuhkan penanganan yang serius oleh pemerintah
termasuk anggaran, penyelenggara, dan tersedianya teknis organisasi perangkat
daerah. Kemajuan Sumber daya manusia (SDM) suatu daerah sangat bergantung pada
pendidikan. Demikian pula kemajuan perekonomian daerah ditentukan oleh
kemampuan pelayanan publik lintas sektoral seperti ketersediaan perbankan
sebagai penyokong modal padat karya, energy, sumberdaya daya alam dan daya
dukung infrastruktur.
Masyarakat
yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung tentu saja tidak bersikap pasif dan pasarh
menerima segala bentuk pelayanan publik melainkan harus memposisikan dirinya
sebagai penyokong dan pendukung utama. Respons balik ini diharapkan mampu
mengawasi fungsi birokrasi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. (***)