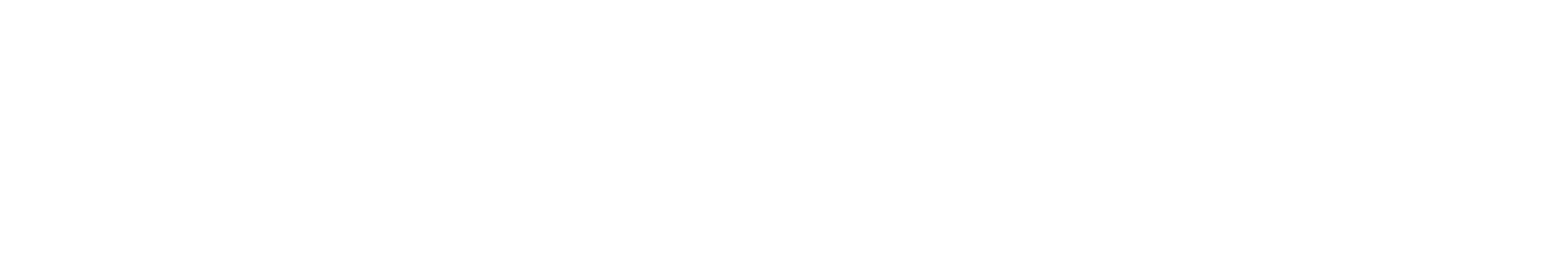Anak Jalanan, Buah Tala, dan Puisi yang Tak Didengar

Oleh: Askim Kanshu
(Sebelumnya, menulis dan menyunting buku dengan nama pena M. Kubais M. Zeen)
Membaca novel debut Hannah Tinti, The Good Thief: Perjuangan Seorang Anak Jalanan Mendapatkan Kasih Keluarga, sembari menyeruput kopi dan mendengarkan lagu-lagu Tegar serta “Si Budi Kecil” dari Iwan Fals, ingatakan saya terpelanting pada seorang anak lelaki di Kota Makassar. Berasal dari Jeneponto, usianya sekitar dua belas tahun.
Awal Mei, saya dan seorang aktivis perlindungan anak bertemu dengannya di kawasan Talasalapang. Di bawah pohon rindang, ia berteduh dari sengatan matahari pukul 12.30. Tak hirau debu dan deru kendaraan. Di bangku bambu, ia letakkan dagangannya: buah tala dan tuak manis, yang setia di pundaknya sepanjang hari.
Tubuhnya kumal. Tatapannya kosong tapi tajam, mengamati anak-anak seusianya yang berlalu dengan seragam sekolah. Raut wajahnya menyimpan rindu akan sekolah, juga masa kecil yang direnggut keadaan.
Kami membeli lima bungkus buah tala dan sebotol tuak manis, lalu membawanya ke kantor yang konsen pada perlindungan anak untuk dibagi, sambil membicarakan ironi yang tak pernah benar-benar usai: anak-anak yang kehilangan hak hidup layak sejak melihat dunia.
Beberapa bulan sebelumnya, saya melihatnya di depan SMP Negeri 30 saat mengantar si sulung dan putri di salah satu sekolah unggulan itu. Ia memikul beban yang sama. Matanya mengikuti anak-anak sekolah, lalu menunduk dan melangkah lesu.
Malam hari, saat toko dan pusat perbelanjaan modern mulai ditutup, saya menjumpainya melahap sebungkus nasi di atas jembatan Jalan Dg. Sirua. Tanpa cuci tangan, dan air bersih. Ia makan dalam diam, dikelilingi asap knalpot kendaraan yang pekat. Di sampingnya, buah tala dan tuak manis setia menemani. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang peduli. Ia pun tampak telah lelah berharap.
Buah tala, dalam bahasa Bugis-Makassar adalah sebutan untuk buah pohon lontar, yang banyak tumbuh di Jeneponto, daerah asalnya. Dikenal sebagai “pohon kehidupan,” karena memberi banyak manfaat: air, makanan, kesehatan, bahkan atap. Usianya mencapai ratusan tahun. Namun bagi anak ini, “pohon kehidupan” laksana simbol ironis. Hidupnya tak pernah tumbuh—terpangkas di akar sebelum mekar.
Cerita lain datang dari Jakarta, tahun 1996, dari seorang anak jalanan bernama Dadang. Ia membacakan puisi tanpa judul dalam sebuah panggung forum, yang dipublikasikan majalah D&R, 17 Agustus 1996:
“Anak jalanan
hidup di emper pertokoan
dengan embun malam hari
tidur tanpa baju…..
diosak-asik tempatnya
ditendang tubuhnya
dilempar ke jalanan…”
Tak hanya puisi. Bersama kawan-kawan sejalannya, Dadang menyanyikan lagu yang juga tak berjudul. Nadanya meluncur dari luka.
“Di atas gedung-gedung bertingkat
di tengah ruang-ruang diskusi
di dalam kamar-kamar istana
kami jadi bahan bicara
dibahas sambil sarapan pagi
bagai barang tak berarti
kami pun dibuang sekenanya…”
“….buka mata hatimu
berkacalah pada wajah di depanmu yang terluka penuh duka
….yang ingin bercerita tentang hilangnya hati manusia
Gelap
dunia ini makin pekat
Hati manusia tak bicara
penuh mega-mega kuasa.”
Dadang dan anak penjual buah tala itu adalah dua wajah dari kepedihan yang sama: kemiskinan. Mereka adalah suara yang jarang didengar, bahkan ketika mereka bersuara lantang.
Penyair Agnes Arswendo pernah menulis dalam sajak “Di Sembarang Kampung” (1976) yang dinukil majalah Tempo, 1993:
“Di sebuah kampung, tak ada batas-batas
Ruang tidur ialah tempat makan dan marah
Kamar mandi milik bersama, dan bau pesing disumbangkan
Beramai-ramai …
Di sembarang kampung
Di kota metropolitan dan bukan
Harapan telah lama dibunuh.”
Setiap negara punya cara menangani anak jalanan. Di beberapa negara Amerika Latin, cara itu bahkan melibatkan peluru. Di negeri ini, tak kalah suram: razia jalanan mendadak ketika ada tamu penting, tim penilai lomba adipura, spanduk larangan memberi uang pada pengemis, hingga rumah singgah yang hanya ramai saat program pemerintah sedang gencar.
Di kota itu, sempat dibangun rumah singgah pada awal reformasi. Posko-posko penjaringan anak jalanan didirikan. Tapi seperti biasa, problem administratif antara instansi terkait di provinsi dan kota, mentalitas korup sebagian birokrat, dan program-program setengah hati hanya menambah luka. Anak-anak tetap di jalan.
Kerap kali kita jumpai pula spanduk-spanduk di persimpangan kota menolak pemberian sedekah kepada anak jalanan. Tapi siapa sebenarnya yang kita tolak? Kemiskinan? Atau nurani kita sendiri?
Anak jalanan adalah potret buram modernisasi dan pembangunan tanpa perasaan—meminjam istilah ekonom Revrisond Baswir. Mereka bukan sekadar anak-anak yang kehilangan rumah, haknya untuk sekolah dan bermain. Tapi cermin retak dari sistem yang gagal. Mereka bukan angka dalam laporan statistik, melainkan manusia.
Akankah si penjual buah tala dan anak-anak jalanan lainnya mampu keluar dari belitan kemiskinan yang “diawetkan” turun-temurun?
Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh yang meraih hadiah Nobel Perdamaian 2008, pernah menjawabnya dengan sederhana: “Untuk menghapus kemiskinan dari dunia ini, hanya dibutuhkan satu hal: niat.” (*)